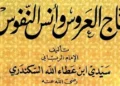Keutamaan Bersuci: Landasan Spiritual dan Pendidikan Karakter
Ibnu Hajar memulai pembahasannya dengan menghadirkan hadis-hadis yang menegaskan keutamaan (fadilah) bersuci, memberikan fondasi filosofis bahwa taharah bukan sekadar rutinitas fisik. Hadis utama yang dikutip adalah riwayat Muslim dari Abu Malik al-Asy’ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ath-thuhuru syathru al-iman” (Bersuci adalah separuh dari iman). Penempatan hadis ini di awal bab bersifat sangat strategis. Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menafsirkan “bersuci” di sini mencakup dua dimensi: suci lahir dari hadas dan najis, serta suci batin dari syirik dan maksiat. Dengan demikian, Ibnu Hajar segera mengangkat diskusi taharah dari level teknis-fikih menuju level spiritual-akidah. Dalam konteks pendidikan Islam, pengajaran taharah yang dimulai dengan pemahaman akan keutamaannya menciptakan paradigma motivasi intrinsik. Santri tidak diajari “cara berwudu” semata, tetapi terlebih dahulu diinsyafkan bahwa aktivitas tersebut merupakan manifestasi dan penyempurna keimanan. Pendekatan ini selaras dengan teori pendidikan yang menekankan meaningful learning, di mana pengetahuan dihubungkan dengan nilai dan makna yang lebih dalam. Penanaman kesadaran bahwa kebersihan fisik berkorelasi dengan kebersihan jiwa akan membentuk karakter muslim yang utuh (insan kamil), yang menghargai kesucian sebagai bagian integral dari identitas keislamannya. Oleh karena itu, pengajaran bab taharah dalam pesantren harus menitikberatkan pada aspek nilai sebelum masuk kepada aspek tata cara.
Klasifikasi Air dan Prinsip Kemudahan dalam Fikih
Pembahasan tentang air (al-ma’) dan jenis-jenisnya menempati porsi penting berikutnya. Ibnu Hajar menyajikan kaidah-kaidah utama melalui hadis-hadis pilihan. Salah satu yang fundamental adalah hadis tentang air laut riwayat Abu Hurairah: “Huwa ath-thahuru ma’uhu, al-hillu maitatuhu” (Air laut itu suci dan menyucikan, bangkainya halal) (HR. at-Tirmidzi, an-Nasa’i). Hadis ini berfungsi sebagai qaidah ushuliyyah (kaidah pokok) yang menetapkan bahwa pada asalnya, seluruh air di muka bumi adalah suci dan menyucikan (thahur). Penegasan ini membatalkan keraguan yang mungkin timbul dan menunjukkan kemudahan syariat. Lebih lanjut, hadis tentang “dua qullah” yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar (HR. al-Khamsah) memberikan parameter praktis: air dalam volume besar (sekitar 200 liter menurut salah satu pendapat) tidak menjadi najis hanya karena kemasukan benda najis kecuali jika berubah salah satu sifatnya (warna, rasa, atau bau). Prinsip ini memiliki implikasi modern yang sangat luas. Dalam pengelolaan sanitasi dan air bersih di fasilitas umum (sekolah, masjid, rumah sakit), kaidah “dua qullah” dapat menjadi pertimbangan fikih untuk menetapkan status air dalam tangki penampungan atau kolam. Bagi santri, memahami diskursus ini melatih kemampuan melakukan kontekstualisasi hukum (al-fiqh al-waqi’i). Mereka diajak untuk tidak hanya menghafal hukum, tetapi juga memahami ‘illat (alasan hukum) di baliknya—dalam hal ini, adalah kesulitan menjaga kemutlakan air dalam volume besar—sehingga dapat menerapkannya dalam situasi kontemporer yang beragam.
Etika Bersuci dan Adab Buang Hajat: Pendidikan Adab dan Kesadaran Sosial
Bab ini juga memuat norma-norma etiket (adab) yang terkait dengan aktivitas bersuci, terutama saat buang hajat. Hadis larangan beristinja’ dengan tulang atau kotoran hewan riwayat Abu Hurairah (HR. al-Bukhari) mengandung pelajaran multidimensional. Di satu sisi, ia mengajarkan prinsip efektivitas dalam menyucikan najis (tulang dan kotoran tidak mampu membersihkan dengan sempurna). Di sisi lain, sebagaimana dijelaskan dalam syarah hadis, terdapat dimensi spiritual berupa penghormatan terhadap makhluk lain (tulang adalah makanan jin). Demikian pula hadis-hadis tentang larangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat di tanah lapang, beserta pengecualiannya di dalam bangunan. Ibnu Hajar dengan cermat menyajikan kedua varian riwayat ini, menunjukkan contoh konkret bagaimana ulama melakukan al-jam’u baina an-nushush (mengompromikan teks-teks yang tampak bertentangan). Pelajaran penting bagi santri adalah bahwa hukum Islam itu lentur dan mempertimbangkan konteks. Larangan berlaku di ruang terbuka untuk menjaga kesakralan arah kiblat, tetapi keringanan diberikan di ruang tertutup yang sudah menjadi tempat khusus (mu’attar) untuk buang hajat. Aspek edukatif di sini adalah pembentukan kesadaran sosial dan etika ruang. Santri diajari untuk selalu mempertimbangkan keberadaan orang lain dan nilai-nilai kesantunan, bahkan dalam aktivitas yang bersifat sangat privat.
Wudu: Integrasi Gerakan, Niat, dan Makna Spiritual
Pembahasan wudu merupakan jantung dari bab taharah. Ibnu Hajar tidak hanya menyajikan tata cara praktis, tetapi juga menyelipkan hadis-hadis yang mengungkap makna spiritual di balik setiap gerakan. Hadis tentang tata cara wudu Utsman bin Affan yang diakhiri dengan sabda Nabi, “Barangsiapa berwudu seperti wuduku ini…” (HR. al-Bukhari dan Muslim), menegaskan pentingnya keteladanan (qudwah) dan kesempurnaan (itqan) dalam beribadah. Lebih mendalam lagi, hadis tentang cahaya anggota wudu di hari kiamat riwayat Abu Hurairah (HR. Muslim) mentransformasikan wudu dari ritual pembersihan menjadi investasi eskatologis. Setetes air yang membasuh anggota tubuh akan berubah menjadi cahaya yang memancar di padang mahsyar. Narasi semacam ini sangat efektif untuk membangun motivasi beragama yang bersifat transendental. Dalam dunia pesantren, penyampaian materi wudu dapat diperkaya dengan dimensi imajinasi spiritual ini, sehingga santri tidak merasa sedang melakukan rutinitas mekanis, melainkan sedang “menyiapkan cahaya” untuk pertemuan dengan Tuhannya. Anjuran bersiwak sebelum wudu, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah (HR. al-Bukhari), juga patut mendapat perhatian. Di sini, Ibnu Hajar menghubungkan kebersihan mulut dengan kesiapan untuk berkomunikasi (berdoa dan membaca Al-Qur’an) dalam salat. Ini adalah contoh bagaimana Islam mengintegrasikan kebersihan personal dengan kualitas ibadah. Hal ini mengajarkan pentingnya menampilkan Islam sebagai agama yang memperhatikan detail dan estetika, sekaligus mendidik peserta didik untuk selalu tampil terbaik dalam setiap ibadah.
Mandi Besar (Ghusl) dan Pendidikan Kesucian Seksualitas
Pembahasan mandi wajib (ghusl al-janabah) dalam Bulugh al-Marām disajikan dengan proporsional dan penuh hikmah. Hadis Ummu Salamah yang menanyakan kewajiban mandi bagi perempuan (HR. Muslim) menunjukkan bahwa pendidikan tentang kesucian dalam Islam bersifat inklusif dan menjawab kebutuhan spesifik masing-masing gender. Dialog terbuka antara Nabi dengan para sahabat perempuan tentang hal yang dianggap privat menjadi teladan bagi pendidik untuk menciptakan ruang aman bagi diskusi tema-tema sensitif dengan penuh etika. Deskripsi praktis mandi Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA memberikan pedoman teknis yang jelas. Namun, yang lebih penting adalah pesan implisit bahwa Islam tidak menganggap hubungan suami-istri maupun keluarnya mani sebagai sesuatu yang kotor atau tercela, melainkan sebagai aktivitas manusiawi yang hanya memerlukan pensucian tertentu sebelum kembali melaksanakan ibadah. Ini merupakan bentuk pendidikan seksualitas yang sehat menurut perspektif Islam. Santri perlu didorong untuk memahami dan kemudian mampu menyampaikan pesan ini: bahwa syariat mengatur pensucian setelah aktivitas seksual bukan untuk menimbulkan rasa bersalah, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara hakikat kemanusiaan dan kelayakan beribadah kepada Allah. Pemahaman ini akan mencegah berkembangnya pandangan negatif terhadap seksualitas dalam diri santri.
Tayamum: Manifestasi Rahmat dan Fleksibilitas Syariat
Bab tayamum menampilkan salah satu keindahan dan kemudahan dalam syariat Islam. Kisah Ammar bin Yasir yang melakukan tayamum dengan berguling di tanah, lalu dikoreksi oleh Nabi SAW (HR. al-Bukhari), sarat dengan pelajaran. Pertama, ia menunjukkan bahwa kesalahan dalam memahami agama—selama didasari pada ikhtiar yang sungguh-sungguh (ijtihad)—dapat dimaklumi dan diberi koreksi dengan lembut. Kedua, hadis ini menetapkan tata cara tayamum yang sederhana: memukulkan telapak tangan ke tanah yang suci, lalu mengusap wajah dan kedua tangan. Prinsip utama yang dapat dipetik adalah bahwa syariat Islam selalu memberikan solusi (rukhas) ketika menghadapi kesulitan (masyaqqah). Ketidakadaan air, keterbatasan air untuk kebutuhan minum, atau kondisi sakit yang membahayakan jika terkena air, semua menjadi alasan yang dibenarkan untuk bertayamum. Bagi santri yang akan hidup di masyarakat dengan beragam kondisi geografis dan sosial, pemahaman tentang fleksibilitas ini sangat krusial. Mereka harus mampu mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang realistis, tidak memberatkan, dan selalu mempertimbangkan kemaslahatan manusia. Tayamum adalah simbol nyata dari ayat “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Al-Baqarah: 185).
Hal-hal yang Membatalkan Wudu dan Pendidikan Kesadaran Diri
Penutup bab taharah membahas tentang pembatal-pembatal wudu. Hadis-hadis yang disajikan, seperti riwayat Busrah binti Shafwan tentang menyentuh kemaluan (HR. at-Tirmidzi) dan riwayat Anas tentang tidur (HR. Ahmad), berfungsi untuk melatih kesadaran diri (muraqabah) seorang muslim. Setiap aktivitas yang membatalkan wudu—keluarnya sesuatu dari dua jalan, tidur nyenyak, hilang akal, atau sentuhan langsung pada kemaluan—mengajarkan individu untuk selalu awas terhadap kondisi tubuh dan kesuciannya. Dalam perspektif pendidikan, ini mirip dengan latihan mindfulness. Seorang muslim diajari untuk selalu hadir secara penuh dalam setiap momen, menyadari perubahan status hukum dirinya, dan segera mengambil tindakan korektif (berwudu ulang) untuk kembali layak beribadah. Proses ini melatih kedisiplinan, ketertiban, dan tanggung jawab pribadi. Lebih jauh, perbedaan pendapat ulama mengenai beberapa pembatal wudu (seperti sentuhan lawan jenis tanpa syahwat) yang juga tercermin dari penyajian hadis-hadis yang berbeda oleh Ibnu Hajar, memberikan pelajaran berharga tentang ikhilaf (perbedaan pendapat) yang ilmiah dan terhormat. Santri diajari untuk menghargai keragaman interpretasi selama berdasar pada dalil yang valid.
DAFTAR REFERENSI
- Al-‘Asqalani, Ibn Hajar. Bulugh al-Marām min Adillati al-Ahkām. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Al-Jami’ ash-Shahih (Shahih al-Bukhari).
- Muslim ibn al-Hajjaj. Al-Jami’ ash-Shahih (Shahih Muslim).
- At-Tirmidzi, Abu ‘Isa. Al-Jami’ al-Kabir (Sunan at-Tirmidzi).
- An-Nasa’i, Ahmad ibn Syu’aib. As-Sunan al-Kubra (Sunan an-Nasa’i).
- An-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. Syarh Shahih Muslim. Kairo: Dar al-Hadits.
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali. Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh ath-Thaharah. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-‘Asqalani, Ibn Hajar. Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari. Kairo: Dar as-Salam.