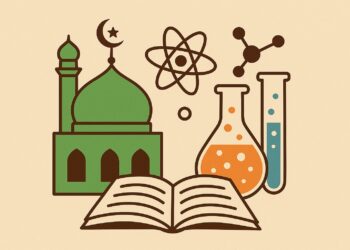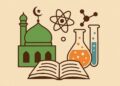يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya’; sebahagian mereka adalah auliya’ bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi auliya’, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al Maidah : 51)
Makna yang berkembang dari kata أَوْلِيَاءَ (dekat) adalah: pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, yang utama dll. Auliya’ sering diterjemahkan sebagai pemimpin, karena seorang pemimpin didukung, dicintai dan dekat dengan yang dipimpinnya. Akan tetapi hasil kajian pada kitab-kitab tafsir klasik (salaf) termasuk at Thabary dan Ibnu Katsir tidak menunjukkan kata auliya’ dalam ayat di atas berarti pemimpin, tetapi maknanya semacam sekutu atau aliansi. Penggunaan kata تَتَّخِذُوا yang artinya mengandalkan diri pada sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang lain, mendukung pemaknaan seperti itu.
Yahudi dan Nasrani yang dimaksud di sini adalah sebagaimana disinggung dalam ayat sebelumnya (Al Maidah : 50), yaitu sebagian Ahlul Kitab yang lebih suka mengikuti hukum jahiliyah yakni tradisi yang didasarkan pada hawa nafsu, kepentingan jangka pendek, kepicikan pandangan serta sesat menyesatkan. Mereka mengabaikan hukum Allah dan bermaksud memalingkan kaum muslimin dari pengabdian kepada Allah. Yahudi-Nasrani atau siapapun yang memiliki sifat seperti ini tidak boleh diambil sebagai auliya’, yakni orang-orang dekat dan terpercaya untuk diandalkan sebagai sekutu.
Auliya’ juga dimaknai dengan cinta kasih yang mengantar kepada menyatunya jiwa yang tadinya berselisih, saling terkaitnya akhlaq dan miripnya tingkah laku. Dua orang yang saling mencintai bagaikan memiliki satu jiwa, satu kehendak, dan satu perbuatan. Pemahaman ini cocok dengan surat Al Mumtahanah ayat 1 :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu…
Kedua ayat ini (Al Maidah : 51 dan Al Mumtahanah : 1) turun dalam konteks peperangan, yaitu perang Uhud dan penaklukan kota Makkah. Tidak ada ulama tafsir, baik klasik atau modern, yang menerangkan ayat ini berkenaan dengan larangan mengangkat seorang non-muslim menjadi pemimpin. Ayat-ayat tersebut melarang orang-orang beriman untuk memberikan loyalitas dan kasih sayang kepada orang kafir sehingga berpotensi mengkhianati perjuangan umat Islam. Hal itu bisa terjadi karena mereka dalam kondisi memerangi atau merugikan umat Islam dengan berbagai cara. Pemahaman seperti ini sebagaimana ditegaskan di ayat yang lain:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi auliya’ dengan meninggalkan orang-orang mukmin… (An Nisa : 144)
Inilah alasan mengapa Umar bin Khattab ketika berkuasa (634-644 M) bersikap tegas kepada orang Nasrani-sebagaimana disebut dalam sebuah riwayat. Pada masa pemerintahannya sedang terjadi konflik bersenjata antara umat Islam dengan Romawi dan Persia. Umar keberatan atas ketergantungan Abu Musa Al Asy’ari, gubernurnya di Bashrah Iraq terhadap orang Kristen dalam bidang pengelolaan administrasi keuangan pemerintahan, termasuk di dalamnya catatan tentang zakat, pajak dan baitul mal. Bagi Sang Khalifah, rahasia negara menjadi beresiko ketika posisi strategis semacam itu dipercayakan kepada non-muslim di masa ekspansi dakwah ke wilayah-wilayah mereka, seperti saat pembebasan Iraq dan Mesir. Sikap tegas Umar ini merupakan bagian ijtihadnya sebagai amirul mukminin. Abu Musa sebagai sesama sahabat utama Nabi saw berbeda pandangan dengan Umar, meskipun sebagai anak buah ia tetap harus mematuhi perintah atasannya.
Dalam kenyataan lain, sebagian non-muslim itu ada yang tinggal dalam komunitas umat Islam, hidup damai tanpa permusuhan, dan tidak ada tanda-tanda yang mengantarkan prasangka buruk kepada mereka. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum muslimin. Tidak ada larangan bahkan justru diperintahkan untuk bersahabat dan berlaku adil kepada mereka, sebagaimana ayat:
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Al Mumtahanah : 8)
Sepanjang peradaban Islam, sejarah mencatat kerjasama di berbagai bidang antara muslim dan non muslim. Mu’awiyah yang berkuasa pada tahun 661 – 680 M, mengangkat tokoh Nasrani Damaskus, pendeta John, menjadi bendahara negara, sebuah posisi yang penting dan strategis setelah panglima militer pada dinasti Umawi. Di Jaman Abbasiyah, khalifah ke-16 al-Mu’tadhid (892 – 902 M), mempercayakan posisi gubernur di Provinsi al-Anbar, Irak kepada seorang Kristen taat, Umar bin Yusuf. Beberapa jabatan pemerintahan di ibukota dan berbagai provinsi dipegang oleh orang Yahudi. Di bidang militer, tentara muslim lebih dari sekali dipimpin oleh jenderal Kristen; yaitu pada masa khalifah Abbasiyah ke-15, al-Mu’tamid dan Khalifah ke-18, al-Muqtadir.
Di zaman kekuasaan sultan Buwayhiyah (934 – 1055 M) menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri keuangan, hingga dokter pribadi khalifah seringkali dijabat oleh orang-orang Kristen. Al Muttaqi (940-944) mempunyai seorang wazir beragama Kristen. Nashr bin Harun, seorang Kristen, ditunjuk sebagai perdana menteri di masa ‘Adud ad-Daulah (949 – 982), penguasa terbesar dinasti Buyid di Iran. Demikian pula halnya di belahan wilayah muslim bagian Barat (Andalus Spanyol) serta pada jaman Turki Utsmani, banyak posisi penting negara dipegang oleh orang-orang Yahudi maupun Kristen.
Imam al Mawardi menjelaskan dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyah bahwa dalam hal kekuasaan pemerintahan berada di tangan kepala negara, dimana kedudukan para menteri hanya sebagai pembantu dan pejabat negara (pegawai pemerintah), maka dibenarkan adanya anggota kabinet atau menteri dari kalangan non-muslim. Muhammad Abduh, tokoh pembaharu dari Mesir menegaskan bahwa larangan mengangkat pemimpin non-muslim itu merupakan larangan yang bersyarat (illat), yaitu ketika mereka (non-muslim) itu orang-orang yang berperilaku buruk kepada umat Islam. Manakala perilaku buruk itu tidak ada, maka larangan tersebut tidak berlaku. Jadi larangan tersebut sama sekali bukan berkaitan dengan perbedaan agama semata.
Memasuki abad modern, geo-politik bergeser secara revolutif dari semula yang bersifat eksklusif menjadi inklusif dengan munculnya konsep republik dan demokrasi. Pasca kemerdekaan, di kalangan warga negara mayoritas muslim banyak yang mendirikan negara republik dengan sistem demokrasi. Indonesia adalah salah satunya, tidak memproklamasikan diri sebagai negara Islam tetapi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pilihan di atas membawa konsekuensi signifikan terhadap konsep kepemimpinan dimana konstitusi (UUD 45) memberikan akses dan partisipasi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan. Pergeseran geo-politik ini layak untuk dipertimbangkan sebagai illat (ratio logis/alasan hukum) yang lebih permanen ketimbang argumen eksklusif bahwa kepemimpinan non-muslim diperbolehkan jika ‘tidak memusuhi’ umat Islam.
Dari tinjauan fiqih siyasah, Al Mawardi (972-1058) mensyaratkan seorang pemimpin harus memiliki kemampuan, berintegritas, adil, berilmu dan berwawasan luas. Syarat lainnya yaitu harus seorang lelaki muslim yang berasal dari keturunan Qurays. Pendapat senada juga disampaikan oleh Al Juwaini (1028-1085) dan Ibnu Khaldun (1332-1406). Ibnu Taymiyah (1263-1328) memiliki pendapat yang berbeda. Ia menegaskan bahwa keadilan merupakan syarat terpenting bagi seorang pemimpin dibandingkan prasyarat yang lainnya. Sedemikian pentingnya tentang keadilan ini sehingga ia mengatakan:
“Sesungguhnya Allah menyokong negara yang adil meskipun kafir (pemimpinnya) dan tidak mendukung negara yang despotik meskipun muslim (pemimpinnya). Dunia dapat tegak dengan memadukan antara kekufuran dan keadilan dan dunia tidak dapat tegak dengan modal kezaliman dan keislaman”.
Referensi:
- M. Quraish Shihab, 2011, Tafsir Al Misbah : Pesan-Kesan-dan Keserasian Al Qur’an, cetakan IV, Lentera Hati, Ciputat-Tangerang
- Nadirsyah Hosen, 2017, Tafsir Al Qur’an di Medsos : Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci Pada Era Media Sosial, Bentang Pustaka, Yogyakarta
- Siti Ruhaini D, 2015, Islam Kepemimpinan non muslim dan HAM, dalam Fikih Kebhinekaan-Maarif Institute, Mizan Pustaka, Bandung
- Wawan Gunawan, 2015, Fikih Kepemimpinan non-muslim, dalam Fikih Kebhinekaan-Maarif Institute, Mizan Pustaka, Bandung
- Philip K Hitti, 2013, History of the Arab, trj. Cecep & Dedy, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta