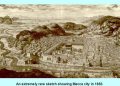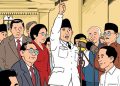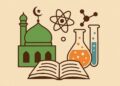Tahun 1970 hingga 1980-an sejumlah ekonom berpendapat sebuah ekonomi dapat dinamakan ekonomi Islam jika mengikuti ketentuan syariah mengenai riba, penolakan bunga bank, asuransi dan persaingan bebas (laisses faire). Kajian ini menarik karena: 1) Bermunculan program yang berlabel syariah seperti Bank Syariah, Asuransi Takaful dll. 2). Ekonomi kita berjalan tanpa menggunakan acuan moral sama sekali (asas kapitalistik). Lantas muncul pertanyaan, apakah sistem yang hanya bertumpu pada acuan moral saja dapat disebut sistem ekonomi? Efisiensi yang dibawakan oleh kapitalisme, yang menjadi inti dari praktik ekonomi yang sehat, apakah bertentangan dengan ajaran Islam?.
Perkembangan gagasan Ekonomi Islam selama ini menunjukkan kemandulan karena lebih cenderung untuk mempermasalahkan aspek-aspek normatif, seperti bunga bank dan asuransi. Lebih berfokus pada pencarian nilai-nilai daripada pencarian cara/aplikasi yang bisa dilakukan oleh nilai-nilai tersebut.
Bank Syariah sebagai eksperimen penerapan Ekonomi Islam masih jauh dari harapan ideal yang dicita-citakan. Bank Syariah seharusnya berbasis perdagangan yang sah dan bebas riba, Kenyataan perbankan di negeri kita, baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktik perniagaan praktis.
Bank Syariah sebagai penyedia dana sesuai aturan harus menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah (Pembiayaan untuk pelaku usaha/punya keahlian tapi tidak punya modal). Pengelola dana (nasabah) bebas dari kerugian apapun, kecuali apabila ada: kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Kenyataan di lapangan nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha.
Praktek di lapangan jarang ditemui akad mudharabah murni, tapi modifikasi mudharabah dan musyarakah (serikat usaha). Hal ini terjadi karena Bank Syariah hanya mau memberikan pembiayaan kepada usaha yang telah berjalan selama kurun waktu tertentu. Pembagian return pembiayaan tidak berdasarkan sistem bagi hasil dan rugi (profit and loss sharing) tetapi menggunakan sistem bagi pendapatan (revenue sharing). Sistem ini dipilih karena Bank Syariah belum sepenuhnya berani berbagi risiko atau kerugian modal secara penuh. Keuntungan yang harus diberikan kepada nasabah ternyata telah dikira-kira (ditetapkan di muka) oleh Bank Syariah.
“Modifikasi akad” seperti ini tidak bisa dielakkan dari praktik perbankan syariah di Indonesia untuk mengakomodir kehendak sistem perekonomian kapitalis yang menaungi mereka, yang tentu saja menghendaki resiko ditekan sekecil mungkin. Menurut data OJK (2016), akad murabahah yang berisiko rendah dan bersifat konsumtif merupakan akad pembiayaan paling laris (61 %). Sedangkan akad investasi berisiko tinggi dan bersifat produktif berada jauh dibawahnya : musyarakah (31,7 %) dan mudharabah (7,29 %). Ini di luar harapan dari tujuan syariah, yaitu pembiayaan dalam rangka menunjang usaha produktif bukan konsumtif.
Problemnya ditambah lagi dengan skala bank syariah yang kecil membuat mereka kurang efisien. BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) lebih tinggi dari konvensional, produktivitas kalah, sehingga akhirnya kalah bersaing dengan bank konvensional. Kondisi inilah yang dikritik oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Budi Gunadi, “Dengan sedih harus saya bilang, Ini bank konvensional KW-2..!”.
Abdullah Saeed (pakar Hukum Islam), juga menyoroti penerapan sistem profit and loss sharing (PLS). Sistem PLS ini, yang ada dalam akad mudharabah dan musyarakah, digadang-gadang menjadi pembeda antara Bank Islam dengan Bank Konvensional yang hanya menerapkan sistem profit sharing saja, tanpa loss sharing. Sitem PLS ini jika bisa diterapkan akan memperlakukan nasabah dengan lebih adil. Jika prinsip yang digunakan ternyata tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, maka upaya pengembangan bank syariah bisa jadi termasuk tahsilul hasil (melakukan hal yang tidak perlu). Sehingga lembaga yang hampir bangkrut seperti Bank Muamalah seyogyanya tidak perlu dipertahankan mati-matian.
Ekonomi Kerakyatan
Dalam ekonomi modern ini kita melihat pelaksanaan prinsip islam (fastabiqul khoirot), yang bisa melahirkan efisiensi. Tetapi orientasi ekonomi kapitalistik mengutamakan individu pengusaha besar dan pemilik modal. Berbeda dengan ekonomi islam yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kita tidak perlu terlalu antipati dengan ekonomi kapitalis. Amerika, biangnya kapitalis saja bisa melakukan modifikasi untuk kepentingan rakyatnya. Presiden Jackson memutuskan mengangkat gubernur bank sentral, agar dapat melakukan pengelolaan dan menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Padahal teori kapitalisme klasik menyatakan pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi nasional. Kebijakan Jackson ini melahirkan Kapitalisme Rakyat (folks Capitalism). Tesa kapitalis melawan antitesa sosialis bisa melahirkan sintesa ekonomi rakyat.
UUD 45 menetapkan tujuan negara yaitu dalam rangka terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam qaidah fiqih disebutkan : thasarruf al imam ala ar raiyyah manuthun bi al maslahah (Kebijakan dan tindakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin harus sejalan dengan kemaslahatan mereka). Sehingga dalam ekonomi berlaku prinsip ekonomi yang berorientasi pada kemampuan berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip ekonomi kerakyatan ini sesuai dengan ajaran islam. Terkait nama tidak begitu penting, substansinya yaitu bisa membawa kesejahteraan ekonomi secara mikro (kebahagiaan dunia-akhirat) dan makro (keadilan dan kemakmuran seluruh bangsa)
Inti dari Ekonomi Islam yaitu melindungi yang lemah dan membatasi yang kuat. Kenyataannya yang berlaku: tatanan ekonomi dan finansial kita hampir seluruhnya cenderung menolong sektor yang kuat dan mengabaikan sektor yang dianggap ekonomi lemah. Ada tiga hal yang penting dalam ekonomi berbasis kerakyatan: 1) orientasi ekonomi yang memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kepentingan orang banyak; 2). Mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan itu, tidak ditentukan format dan bentuknya. 3) Pemerintah sebagai penguasa harus memberikan perlindungan kepada yang lemah tanpa melakukan intervensi dalam perdagangan.
Kebijakan ekonomi kerakyatan bisa ditempuh dengan mengembangkan ekonomi rakyat dalam bentuk memperluas dengan cepat inisiatif mendirikan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), dalam bentuk kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas dan sistem kredit sangat murah bagi perkembangan UKM. Dibarengi dengan peningkatan pendapatan ASN dan militer untuk meningkatkan kemampuan daya beli (purchasing power) mereka. Pemerintah perlu langsung memimpin tindakan ini sambil membiarkan perusahaan besar untuk tetap mandiri, dan tetap berpegang pada persaingan bebas, efisiensi dan permodalan swasta dalam dan luar negeri.
Ketika menjadi ketua PBNU Gusdur berusaha merealisasikan ekonomi kerakyatan dengan menggarap proyek ekonomi UKM, seperti uasaha pengalengan nanas, pabrik tapioka, budidaya ikan air tawar dll. Dirintis juga kerjasama antara NU dan Bank SUMMA dengan mendirikan kantor cabang bank NU-SUMMA di seluruh Indonesia, meski pada perjalanannya gagal karena dihambat oleh rejim ORBA. Ketika menjadi presiden, Gusdur juga menaikkan gaji PNS secara signifikan. Ini salah satu contoh misi penerapan ekonomi kerakyatan di lapangan, yang bisa dilanjutkan.
Daripada membuat trik/manipulasi untuk mensiasati syariat demi menjaga tafsir riba tetap hidup di konteks modern, lebih baik umat Islam meninjau kembali aspek moral yang ada dalam syariat larangan riba di zaman pra Islam, mempertimbangkan kembali data-data historis dan kontekstual yang ada, dalam rangka membangun penafsiran yang relevan secara kontekstual yang bisa didukung dan diikuti. Perbankan konvensional yang berbasis kapitalis diupayakan agar berorientasi kerakyatan melalui dukungan penuhnya untuk pengembangan UKM.